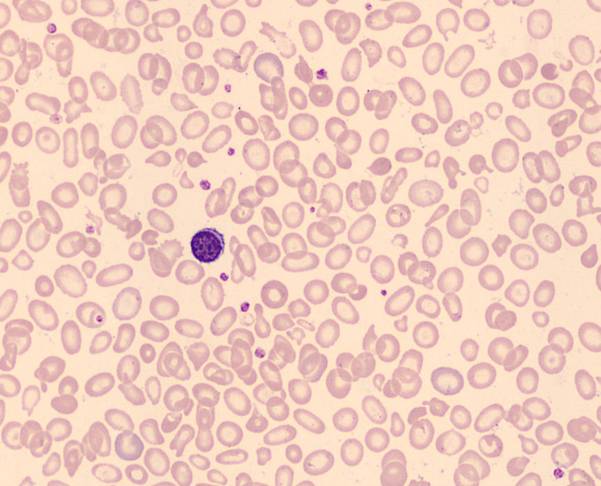Tujuan percobaan ini adalah membuat preparat irisan organ
hepar, intestinum, dan ren pada mencit (Mus musculus) melalui
penyelubungan dengan media paraffin. Pada dasarnya metode irisan ada 2 macam
yaitu metode irisan dengan tangan dan metode irisan dengan mikrotom. Dengan
metode mikrotom hasil irisan lebih tipis dan ketebalannya dapat disesuaikan
dengan keinginan.
Tahap awal dari percobaan ini adalah narcose
(pembiusan), setelah dibius kemudian dilakukan sectio (pembedahan) untuk
diambil hepar, intestinum, dan ren-nya.Organ yang sudah diambil kemudian
dimasukkan ke dalam garam fisiologis (NaCl 0.9%), tujuannya adalah untuk
mempertahankan sel dalam jaringan agar tidak mudah rusak dan membersihkan organ
tersebut dari kotoran, darah, maupun rambut-rambut yang masih menempel. Masing
organ dipotong dengan ukuran tertentu lalu potongan organ dimasukkan ke dalam
larutan fiksatif bouin. Larutan fiksatif ini mengandung asam pikrat jenuh,
aquades 75 ml, asam asetat glacial 5 ml, dan formalin 40% 5 ml. Larutan ini
dapat melakukan penetrasi dengan cepat sehingga nucleus dan jaringan akan
terpulas dengan baik.Tetapi perendaman ini tidak boleh terlalu lama karena akan
menyebabkan jaringan menjadi rapuh atau sulit di iris. Fiksasi bertujuan
untuk mencegah autolysis dan pembusukan oleh bakteri serta mempertahankan
bentuk sel. Asm pikrat dalam dalam larutan bouin berfungsi sebagai zat warna
yang akan menberikan warna kuning dalam jaringan. Langkah selanjutnya adalah washing
dengan alcohol 70% yang berfungsi untuk menghilangkan warna kuning pada organ
setelah fiksasi.
Langkah selanjutnya adalah dehidrasi yang bertujuan
untuk menghilangkan molekul air dan menggantinya dengan molekul alcohol.
Molekul air harus ditarik keluar karena paraffin dan air tidak dapat bercampur.
Dehidrasi delakukan dengan alcohol bertingkat. Tujuannnya adalah agar tidak ada
perubahan secara tiba-tiba terhadap sel yang dapat menyebabkan kerusakan
struktur sel. Proses ini dilakukan + 30 menit setiap kali perendaman.
Jika dilakukan terlalu lama dapat menyebabkan pengerasan pada jaringan.
Langkah selanjutnya adalah clearing, bertujuan untuk
menjernihkan potongan jaringan. Dalm proses ini menggunakan toluol. Toluol
dapat bercampur dengan paraffin maupun dehidran (alcohol). Kelebihan dari
penggunaan toluol adalah perosesnya cepat dan hasilnya bagus (jernih), namun
jikaterlalu lama dapat mengeraskan jaringan. Clearing disebut juga
dealkoholisasi jika dehidrannya alcohol.
Proses selanjutnya adalah infiltrasi yaitu
penyisipan cairan paraffin ke dalam jaringan.Tujuan dari proses ini adalah
untuk mengadaptasikan dengan media paraffin. Caranya adalah masukkan organ ke
dalam larutan xylol:paraffin (1:1) selama 1 jam di dalam oven dengan suhu
55°-60°C. Jika infiltrasi dilakukan di bawah suhu 55°C maka paraffin cair akan
cepat membeku dan jika dilakukan pada suhu di atas 60°C maka organ dapat
matang. Setelah itu, organ dimasukkan ke dalam larutan paraffin I, paraffin II,
dan paraffin III masing-masing selama 30 menit. Pemindahan harus dilakukan
secara cepat agar paraffin tidak membeku.
Proses selanjutnya adalah embedding (penanaman
jaringan ke dalam blok paraffin), saat penanaman perlu diperhatikan posisi dari
organ, apakah tujuannnya ingin mendapatkan penampang melintangnya atau
penampang bujurnya. Pada organ intestinum di tanam dalam posisi berdiri karena
akan dibuat penampang melintangnya, sedangkan untuk hepar dan ren dalam
diletakkan sembarang karena struktur selnya sama di semua sisi. Pada cetakan
dituang sedikit paraffin setelah itu diletakkan organnya kemudian dituang
parafinnya dan diletakkan kaset parafinnya. Setelah itu di diamkan dan di
masukkan ke dalam freezer agar paraffin cepat mengeras. Setelah itu blok
paraffin di lepas dari cetakannya.
Langkah selanjutnya yaitu sectioning dengan mikrotom.
Dilakukan dengan cara menempatkan kaset paraffin pada holder mikrotom kemudian
ketebalan ditentukan pada ukuran 6µm, setelah siap baru dilakukan mikrotoming
hingga semua potongab organ pada paraffin teriris. Hasil dari proses mirotoming
di tamping dengan kertas dan irisan-irisan ini disebut coupes. Hasil
mikrotoming terkadang terlihat menggulung dan pecah, hal ini kemungkinan
disebabkan kerena proses infiltrasi kurang sempurna atau karena proses
embedding kurang tepat.
Proses selanjutnya adalah affixing yaitu penempelan
coupes pada gelas benda. Sebelum dilakukan affixing gelas benda dibersihkan
terlebih dahulu kemudian diolesi dengan albumin meyer. Komposisi albumin meyer
adalah albumin telur 50 ml, gliserin 50 ml, dan natrium salisilat 1 gr. Albumin
meyer berfungsi untuk merekatkan coupea dengan gelas benda. Jika coupes
terlihat mengkerut, maka sebelum diletakkan di atas gelas benda coupes-coupes
ini diletakkan terlebih dahulu di atas air hangat untuk menghilangkan kerutan.
Kemudian setelah coupes lurus baru diambil dengan gelas benda secara langsung,
dimana gelas benda terlebih dahulu di olesi dengan albumin meyer. Diusahakan
coupes berada tepat di tengah-tengah gelas benda agar nantinya mudah diamati.
Proses selanjutnya adalah deparafinasi yang bertujuan
untuk menghilangkan paraffin yang masih menempel. Untuk menghilangkannya di
gunakan xylol karena xylol dapat melarutkan paraffin. Deparafinasi dilakukan
melalui 2 tahap yaitu merendam preparat dalam larutan xylol I selama 15 menit
dan larutan Xylol II selama 5 menit. Hal ini bertujuan agar paraffin
benar-benar hilang.
Tahap selanjutnya adalah Staining (pewarnaan), pewarna
yang di gunakan yaitu HE (Hematoxylin Eosin). Hematoxilin akan mewarnai inti
sel menjadi ungu atau merah sedagkan Eosin akan mewarnai sitoplasma
sitoplasma menjadi merah muda. Hematoxylin merupakan pewarna
suksedan yaitu zat warna yang diberikan secara
bergantian (terpisah). HE merupakan pewarna yang bersifat asam sehingga dapat
terjadi pewarnaaan regresif. Oleh karena itu, sebaiknya digunakan deferensiator
basa yaitu bahan yang bersifat alkali, dalam hal ini digunakan Hematoxylin
Ehrlich yang mempunyai komposisi Hematoxylin (0,67 gr), alcohol absolute (33
ml), akuades (33 ml), gliserol (33 ml), dan asam asetat glacial (3,3 ml).
Hematoxylin yang paling baik digunakan adalah pada saat warnanya ungu karena
pada saat itu hematoxylin baru teroksidasi sebagian. Hematin pada Hematoxylin
mempunyai afinitas kecil terhadap jaringan Gliserin yang terkandung dalam
Hematoxylin Ehrlish yang berguna untuk mencegah overstain dan memperlambat
proses pewarnaan. Sedangkan asam asetat glacial berfungsi untuk menaikkan
intensitas zat warna serta mencegah pewarnaan komponen sitoplasma. Alkohol
absolute serta akuades membantu proses ripening dari hematoxylin.
Eosin adalah zat warna golongan xantine yang mempunyai
molekul yang terdiri dari molekul guinonoid yang dihubungkan oleh cincin
nonquinonoid oleh atom C dan O. Eosin digunakan sebagai background stain atau
counter stain yaitu zat warna yang berfungsi untuk memberikan warna kontras
dengan zat warna yang diberikan lebih dahulu. Jika eosin diberikan dalam konsentrasi
yang tinggi akan menghilangkan warna dari zat warna basa.
Tahapan pewarnaan yaitu mula-mula jaringan dibawa ke alcohol
bertingkat dari tinggi ke rendah, yakni alcohol 96%, 90%, 70%, 60%,
masing-masing cukup 1 celupan. Kemudian dimasukkan ke dalam akuades. Tahap ini
bertujuan untuk pengadaptasikan jaringan ke kondisi basa karena sifat
hematoxylin adalah basa. Setelah dimasukkan ke aquades langkah selanjutnya
adalah dimasukkan ke dalam larutan Hematoxylin selama + 5 detik, jika
terlalu lama warna akan sangat pekat dan menyebabkan sulit dibersihkan, selain
itu dapat menyebabkan jaringan menjadi keras akibat oksidasi hematin. Kemudian
dibersihkan dengan air yang mengalir selama 10 menit. Langkah selanjutnya yaitu
pewarnaan dengan Eosin, mula-mula dimasukkan ke dalam aquades lalu dimasukkan
ke alcohol bertingkat dari rendah ke tinggi,yaitu 60%, 70%, hal ini bebagai
bentuk pengadaptasian ke kondisi eosin 2 % dalam alcohol 70 % lalu dimasukkan
ke dalam pewarna eosin selama 3 menit. Tahap selanjutnya dimasukkan ke dalam
alcohol 70%, 80%, 90%, dan 96% masing-masing 1 celupan. Kemudian di rendam ke
dalam xylol selama 15 menit untuk proses penjernihan (clearing).
Langkah selanjutnya adalah mounting dengan
menggunakan enthelan. Enthelan bersifat non aquosa dan larut dalam xylol. Enthelan
dipilih sebagai mounting agen karena dapat merekatkan jaringan ke gelas benda
dan penutup, mempunyai indeks refraksi
yang cukup tinggi, tidak berwarna, dan bersifat netral serta non aquosa
sehingga tidak merusak jaringan.
Tahap terakhir adalah labeling yaitu memberikan
keterangan preparat, dengan cara di tempel pada salah satu sisi gelas benda. Ditulis
jenis penampangnya, nama organ, nama spesies, dan pewarnaan dan perbesarannya berapa.